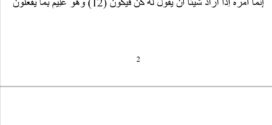Tulisan berikut merupakan lanjutan dari tanggapan saya sebelumnya. Agar lebih mudah, silahkan baca teks asli berikut:
Tulisan berikut merupakan lanjutan dari tanggapan saya sebelumnya. Agar lebih mudah, silahkan baca teks asli berikut:
Ini dikarenakan pada masa itu terdapat dua mazhab hukum, yaitu ahlu al-hadis yang cenderung tektualis dan ahlu al-ra’yi yang cenderung tidak membatasi penggunaan ra’yu (akal atau opini).
Kepentingan ahl al-ra’yi dan ahl al-hadis pada masa Imam Hanafi, Malik dan as-Syafi’i sarat dengan kepentingan politik sehingga bangunan keilmuan Islam awal pun tidak lepas dari pesoalan politik yang memengaruhinya. Contohnya, mengapa Imam Malik (711-795 M) lebih menekankan penggunaan tradisi penduduk Madinah dalam membuat ketetapan hukum? Hal ini disebabkan perpindahan kekuasaan dalam pemerintahan Islam yang tidak lagi ber-ibu kota di Madinah. Untuk merebut otoritas pemegang penetapan hukum (konstitusi) maka tradisi Madinah (ulama Madinah) harus dijadikan acuan. Sedangkan Imam Hanafi atau Abu Hanifah (699-767 M) yang juga guru Imam Malik, tidak menjadikan tradisi penduduk Madinah sebagai acuan pembuat hukum karena ulama Madinah secara geopolitik sudah terpinggirkan dan tidak memiliki power.
Imam Hanafi juga menetap di Baghdad dan Kufah yang ada di Irak, karenanya penetapan hukum yang merupakan asas pembuatan aturan dalam pemerintahan Islam tidak harus merujuk pada penduduk Madinah, tetapi cukup dengan Alquran, Sunnah dan akal. Adapun Sunnah tidak harus susah-payah dilacak hingga sampai pada penduduk Madinah. Sedangkan posisi asy-Syafi’i yang di akhir hidupnya tinggal di Mesir, notabene “meminta jatah” dalam geopolitik saat itu. Karenanya, bangunan fiqh-nya tidak condong ke kubu tekstualis maupun rasionalis. Ia berusaha untuk melakukan kolaborasi antara dua pola pikir tersebut dengan menawarkan metode qiyas sebagai cara penggalian hukum dari sumber-sumber utama seperti Alquran dan Sunnah.
http://www.siperubahan.com/read/1444/Pengaruh-Filsafat-Yunani-dalam-Pemikiran-Hukum-Islam
—
Mari kita kaji pelan-pelan. Benarkah bahwa ahlul hadis sangat tekstualis?
Ahlul hadis adalah para ulama yang berpegang teguh kepada hadis Nabi dalam melakukan ijtihad untuk mencari kesimpulan hukum. Umumnya mereka berada di hijaz (Makah dan Madinah). Hal ini, karena hadis Nabi Muhammad saw banyak berada di tangan mereka. Para sahabat banyak yang tinggal di Hijaz sehingga ketersediaan hadis nabi sangat banyak. Jika bukan hadis secara langsung, maka mereka menyaksikan prilaku sahabat yang telah melihat dan hidup bersama dengan Rasulullah saw. Para sahabat sendiri akan melakukan sesuatu yang sesuai dengan perintah dan larangan Rasulullah saw. Pada akhirnya, prilaku kolektif tersebut membentuk sebuah tradisi di masyarakat Madinah. Imam Malik menjadikan tradisi masyarakat Madinah sebagai salah satu piranti ijtihad, karena bagi Imam Malik, tradisi mereka memang berangkat dari tradisi yang berkembang pada masa Rasulullah dan mendapatkan persetujuan oleh Rasulullah saw.
Jadi penggunaan tradisi penduduk Madinah sebagai piranti ijtihad, bukan karena untuk mencari otoritas pemegang penetapan hukum (konstitusi) yang sudah pindah ke kota lain. Juga bukan karena Madinah yang secara geopolitik sudah terpinggirkan dan tidak memiliki power. Penggunaan tradisi masyarakat Madinah, karena memang masyarakat Madinah adalah masyarakat yang mewarisi tradisi Nabi Muhammad saw.
Apakah mereka tekstualis? Tentu saja tidak. Disebut ahlul hadis, bukan karena pemahaman mereka yang sangat tekstualis, namun karena banyaknya fatawa yang dikeluarkan dengan sandaran pada hadis nabi. Dari sini penggunaan logika yang terlalu luas kurang dibutuhkan. Sederhananya, apa yang ada pada diri mereka, sudah cukup untuk menjadi bahan ijtihad.
Lagi pula, mereka juga menggunakan akal. Terbukti bahwa mazhab Mailiki terkenal dengan penggunaan istihsan dan maslahah mursalah. Kedua model ijtihad tadi merupakan bagian dari ijtihad dengan akal. Jadi tidak selamanya benar bahwa Malikiyah yang tinggal di Madinah terkesan tekstual dan mengesampingkan akal.
Bagaimana dengan Abu Hanifa?
Jika kita lihat, bahwa pioner Ahlurra’yi adalah imam Abu Hanifah. Beliau tinggal di Kufah. Kota ini, cukup jauh dari Madinah, tempat di mana Rasulullah dan para sahabat tinggal. Kufah dulunya juga wilayah kekuasaan Persia.
Dari sisi agama, sebelumnya mereka juga menganut banyak aliran kepercayaan dari Zorowaster, shabiun, Majusi dan lain sebagainya. Aliran kepercayaan tadi, tidak dijumpai di masyarakat Madinah.
Banyak orang-orang yang mengaku Islam, namun pada dasarnya mereka hanya ingin menghancurkan Islam dari dalam. Dari sini berimplikasi pada keadalahan (tingkat kepercayaan) seseorang. Jika masyarakat Madinah banyak yang dapat dipercaya, kondisi ini berbeda dengan di kota Kufah. Para pemalsu hadis bergentayangan di sana.
Persoalan yang muncul di Kufah juga berbeda dengan yang muncul di Madinah. Kufah lebih metropolitan. Apalagi memang sebelumnya ia masuk wilayah ajam (bukan Arab).
Untuk memecahkan persoalan yang ada di Kufah, tentu berbeda dengan cara memecahkan persoalan di Madinah. Abu Hanifah tidak cukup dengan berpedoman pada hadis nabi secara leterleks saja. Apalagi seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, pembawa hadis Nabi (rawi hadis) benar-benar harus diseleksi secara ketat dan tidak serta merta dapat dipercaya. Ini saja sudah menjadi argumen mengapa dalam penggunaan hadis, Abu Hanifah lebih ketat, sementara penggunaan akal lebih luas.
Abu Hanifah melakukan ijtihad dengan akal, namun tetap dengan batas-batas tertentu sesuai dengan metodologi yang beliau terapkan. Kiyas pun, sesungguhnya bukan penggunaan akal tanpa batas. Kiyas hanya upaya ijtihad untuk mencari solusi hukum atas suatu kejadian yang belum ada dalam nas, namun ada hukum lain yang mempunyai illat sama yang sudah ada hukumnya dengan nas. Jadi, kiyas pun tetap dibatasi dengan nas, bukan berfikir bebas tanpa batas.
Apakah kiyas didahulukan dari khabar ahad? Jika kita lihat dari fikih Hanafi, ternyata tidak selamanya demikian. Menurut Imam Abu Zahra, seperti yang beliau tulis dalam kitabnya “Abu Hanifah”, beliau menyatakan bahwa Abu Hanifah tetap menggunakan hadis ahad. Ini terbukti dengan banyaknya riwayat dan istinbath hukum dari hadis ahad seperti yang difatwakan oleh muridnya, Abu Yusuf.
Sebagian ulama Hanafiyah berpendapat bahwa mereka tetap mendahulukan khabar ahad dari kiyas, jika perawinya fakih. Jika perawi hadisnya tidak fakih, baru kemudian kiyas lebih didahulukan dari khabar ahad. Kefakihan ini penting, karena pengaruh sosial pada waktu itu. Banyak pembawa riwayat hadis yang memang harus diteliti terlebih dahulu.
Apakah sunnah tidak harus dilacak sampai Madinah? Sesungguhnya pertanyaan ini sangat menggelikan. Kajian sunnah, minimal ada dua bagian, yaitu dirayah dan riwayah. Dirayah adalah mengkaji sunnah dari sisi matannya, sementara riwayah adalah kajian hadis dari sisi perawinya. Ilmu dirayah dan riwayat kemudian berkembang pesat yang tujuan akhirnya adalah untuk mengkaji kesahihan sebuah hadis nabi. Jadi dalam sejarah pengkajian sunnah, tidak ada syarat harus merujuk hingga ke Madinah.Jika secara matan dan riwayatnya shahih, maka ia tetap harus diterima.
Bagaimana dengan Imam Syafii? Beliau mengkompromikan antara dua model itjihad sebelumnya, yaitu ijtihad dengan akal dan nas. Imam Syafii lantas membukukan metodologi ijtihad secara rapi dengan menulkis kitab ushul fikih Arrisalah. Kitab ini, dianggap sebagai buku ushul fikih pertama yang ditulis secara sistematis dalam sejarah fikih Islam.
Ringkasnya, dalam kajian fikih Islam, para ulama mengeluarkan kemampuan sekuat tenaga untuk menggali hukum Islam dari al-Quran dan Sunnah. Mereka bukan tipe ulama dunia yang mengejar kekuasaan. Bahkan Abu Hanifah harus berhadapan dengan penguasa khalifah al-Manshur dan masuk ke dalam penjara.
Abu Hanifah meninggal setelah mendapatkan siksaan selama di penjara. Apakah Anda tau mengapa Abu Hanifah dipenjara dan disiksa? Abu Hanifah ditawari untuk menjadi Hakim Agung (qadhi), namun menolak. Beliau dipenjara dan dipaksa untuk menerima jabatan tersebut hingga berakibat pada kesyahidan beliau.
Jadi di mana kue kekuasaaan? Salah fatal jika mengkaji fikih Islam dengan menggunakan dialektika materialis. Ulama Islam bukan tipe para intelektual yang mudah terpengaruh dengan kue kekuasaan. Mereka mengkaji Quran sunnah dengan metodologi yang sangat obyektif. Jangan dikira bahwa metodologi yang mereka letakkan tadi, merupakan bias dari realitas sosial dan keinginan untuk mendapatkan otoritas kekuasaan. Jika ingin kekuasaan, dari awal Abu Hanifah menerima jabatan yang ditawarkan oleh khalifah tanpa harus mengorbankan jiwanya.
Kesimpulannya, kajilah sejarah fikih Islam dengan kacamata masyarakat Islam. Jika kita mengkaji Islam dengan kacamata Barat, maka kajian keislaman akan sangat bias dan tidak obyektif. Setiap bangsa mempunyai kultur yang berbeda-beda. Kultur yang berkembang di Barat, berbeda dengan kultur yang berkembang di dunia Islam. Kajian keislaman dengan metodologi Barat yang tumbuh berkembang dari sosiokultural Barat, hanya akan “membaratkan” materi keislaman dan menghilangkan nilai obyektifitas. Wallahu a’lam.