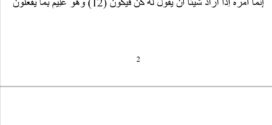Maqashid syar’i adalah tujuan umum dari berbagai hukum dalam syari’ah. Menurut Ibnu Qoyim bahwa tujuan utama diturunkannya hukum syar’i adalah demi kemaslahatan manusia serta menghindari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesengsaraan (madlorot) bagi manusia. Namun demikian bukan bearti maslahat di sini berdasarkan penilaian manusia, namun maslahat dalam pandangan syari’at. Manusia sering terpengaruhi oleh hawa nafsu sehingga penilaian terhadap suatu mashlahah sangat subyektif. Manusia sering kali mengira bahwa sesuatu dapat memberikan manfaat bagi dirinya, padahal yang terjadi adalah sebaliknya, dapat menimbulkan kesengsaraan. Kalaupun dapat memberikan manfaat, madhorotnya lebih besar. Manusia juga sering mengedepankan kepentingan pribadi dengan mengorbankan kepentingan umum, atau mencari maslahat yang bersifat temporal dengan mengorbankan maslahat yang bersifat abadi. Bagaimanapun juga, kondisi psikologis manusia akan berpengaruh terhadap sikap dan arah pemikirannya. Oleh karena itu, menurut Qardhâwî, maslahat yang sebenarnya adalah maslahat yang dilandasi dari hukum syar’i.[1]
Maslahat dalam suatu hukum syar’i dapat diketahui dari zhahir nas yang bersifat sharih (jelas). Hanya saja, nas tidak mencakup semua tujuan dasar dari ketentuan hukum. Menurutnya, hanya mereka yang mempunyai pemahaman mendalam mengenai ilmu maqhashid yang dapat mengetahui kandungan yang tersirat dari nas tersebut. Khusus mengenai fikih ibadah, para ulama tidak merasa perlu mencari tujuan dasar atas perintah ibadah, karena ibadah berkaitan dengan interaksi manusia dengan Tuhan. Maka dalam fikih ibadah para ulama meletakkan kaidah fikih
الْاَصْلُ فِى اْلعِبَادَة التًعَبًُّد وَاْلِالتِزَام النَّصِ
Artinya: Landasan hukum dalam beribadah adalah menyembah Allah serta mengikuti apa yang tertera dalam nas.
Lain halnya dengan fikih mu’amalah yang memerlukan pemahaman terhadap illah serta tujuan tasyri’inya. Dalam hal ini para ulama ushul meletakkan kaidah fikih:
الأصْلُ فِى اْلعَادَاتِ وَالمُعَامَلَاتِ اْلاِلْتِفَاتِ اِلَى اْلمَعَانِي وَاْلمَقَاصِد
Artinya: Prinsip hukum mengenai tradisi dan interaksi dengan manusia adalah melihat maksud dan tujuan.[2]
Maslahat dikelompokkan ke dalam tiga tingkatan:
- Dharûriyât (kebutuhan primer)
- Hâjiyât (kebutuhan sekunder)
- Tahsîniyât (kebutuhan eksekutif)
Dharûriyat adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, dan jika hal itu hilang dari manusia akan menimbulkan ketimpangan dan kekacauan dalam masyarakat sehingga manusia akan sengsara baik di dunia maupun di akhirat.[3] Para ulama klasik mengelompokkan dhorûriyât ke dalam lima tingkatan:[4]
- Hifdz al-din (menjaga agama)
- Hifdz al-nafs (menjaga jiwa)
- Hifdz al-aql (menjaga akal)
- Hifdz al-nasl (menjaga keturunan)
- Hifdz al-mâl (menjaga harta)
Imam Ibnu Asyur menambahkan “al-hurriyah” (kebebasan), sementara Muhammad al-Ghazali menambahkan “al ‘adâlah” (keadilan) wa’l masâwah (kesetaraan).[5] Qaradawi juga menyerukan rekonstruksi ilmu maqashid baik dalam tataran metodologi ataupun materi.[6] Contoh dharûriyât adalah kewajiban melaksanakan shalat, memerangi para penyebar bid’ah dan lain sebaginya demi menjaga eksistensi agama, ketentuan hukuman qishas bagi pembunuh demi menjaga keselamatan jiwa, kewajiban memotong tangan pencuri demi menjaga keselamatan harta, dilarang meminum khamer karena dapat merusak akal, dan dilarang berzina karena dapat merusak keturunan, dan demikian seterusnya.[7]
Dhorûriyât yang merupakan kebutuhan primer bagi umat manusia tidak hanya terdapat dalam ajaran Islam, namun juga agama samawi lainnya. Karena memang berkaitan erat dengan keselamatan dan keamanan manusia. Maka Islam sebagai agama samawi terakhir sangat memperhatian dan memberikan prioritas pada masalah ini.[8]
Kaidah dasar dalam ilmu ushul, termasuk juga kaidah fikih sebenarnya muncul dari pemahaman ulama atas maqashid ‘ammah (tujuan global) dalam syari’at. Kaidah ushul dan kaidah fikih merupakan landasan teoritis bagi para mujtahidin dalam melakukan penggalian hukum. Qaradawi sebagai salah seorang mujtahid, dalam penggalian hukum syar’i tidak pernah lepas dari kaidah dasar tersebut, sebagaimana dapat kita lihat jelas dari berbagai karyanya.
Demi menjaga eksitensi lima hal di atas, para ulama meletakkan berebapa kaidah fikih, diantaranya adalah “al dhorûrot tubîhu al mahdhûrot, al dlorûrot tuqaddaru bi qadrihâ, idzâ dhoqot ittasa’at” dll. Maka sesuatu hal yang sebenarnya diharamkan syari’at jika memang kondisi mendesak dan merupakan satu-satunya jalan untuk menyelamatkan jiwa, seperti makan daging babi di tengah padang pasir, hukumnya menjadi wajib.
Dalam banyak bukunya, Qaradawi memberikan perhatian lebih terhadap maqashid ‘ammah (tujuan global) dalam syari’at serta selalu mengaitkan nas-nas al juz’iyah, yaitu nas yang sudah menjelaskan secara rinci mengenai suatu hukum, dalam ruang lingkup nusus maqasid syar’i al kuliyât, yaitu nas yang hanya memberikan rincian global.[9]
Menurutnya, memahami ilmu maqashid bagi seorang musjtahid, adalah suatu keharusan. Namun demikian ilmu maqashid belum mendapatkan kajian secara serius. Qaradawi dalam berbagai karyanya selalu mengingatakan pentingnya pendalaman ilmu ini serta selalu menghimbau para tokoh cendekia agar memposisikan ilmu maqashid sebagaimana mestinya. Karena menurutnya, pemahaman yang salah terhadap ilmu maqashid akan berdampak pada pemberian fatwa yang salah juga.[10]
Qaradawi membagi pemahaman para ulama terhadap nas
menjadi tiga aliran;
- Kaum literalis. Mereka yang memahami nas secara literal tanpa melihat lebih jauh tujuan dasar diturunkannya hukum syari’i. Qaradawi menamakan aliran ini dengan istilah neo Zahiriyyah (dhahîriyatu’l judud). Mereka seperti penganut mazhab dhahîrî klasik yang menolak ‘illah dalam hukum syariat serta enggan untuk mengaitkan hukum dengan ilmu maqashid. Bagi Qardawi, pamahaman tekstualitas seperti ini dapat berakibat pada kebekuan pemikiran umat Islam.
- Kaum liberalis. Kebaliakan dari aliran pertama, yaitu mereka yang mengklaim dirinya sebagai orang yang salalu memahami nas sesuai dengan ilmu maqashid. Jargon yang sering mereka dengungkan adalah bahwa yang terpenting dalam urusan agama adalah pemahaman substansi dari teks dan bukan teks redaksi dari nas. Mereka tidak membedakan antara dalil qath’i dan dzanni. Bahkan mereka cenderung menafsirkan nas sesuai dengan kepentingan mereka. Jika mereka menghadapi nas sharih, sementara bertentangan dengan arah pemikiran mereka, maka nas tersebut akan ditakwil. Akibatnya adalah pemahaman yang salah dan terkesan ngawur terhadap tek-teks al-Qur’ân maupun Sunnah. Ironisnya mereka mengklaim dirinya sebagai kaum reformis. Corak pemikiran mereka menjadi sangat liberal.
- Moderat. Mereka adalah aliran yang memahami nas secara moderat, tidak literal namun juga tidak liberal. Mereka memahami nas juz’î sesuai dengan maqashid kulî, mengembalikan permasalahan furu’iyah ke dalam nas kuliyah, selalu berpegang kepada nas qoth’i tsubut dan dalâlah, menghindari nas mutasyabbihât dan kembali kepada nas muhkamât. Qaradawi sendiri mengklaim dirinya sebagai pengikut aliran ini. Menurutnya, aliran inilah yang paling mampu mengekspresikan hakikat Islam serta dapat menyelamatkan ajaran Islam dari perubahan dan penyelewengan yang dilancarkan musuh Islam.
Aliran pertama, yaitu mereka yang terlalu literal, menurut Qaradawi banyak merugikan dakwah Islam dan menghalangi penerapan syari’ah Islam. Di samping itu, pemahaman literal dapat merusak citra Islam dari pandangan kaum pemikir kontemporer karena terkesan bahwa Islam adalah agama jumud dan tidak dapat berkembang sesuai dengan tempat dan waktu.
Pemahaman tekstualitas juga berakibat pada ketidak-mampuan mereka dalam menghadapi problematika kontemporer, seperti soal ekonomi, politik, sikap deskriminatif terhadap kaum wanita, mengharamkan wanita memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, dan lain sebagainya. Parahnya lagi mereka berusaha menerapkan fikih klasik dalam realitas kontemporer tanpa melihat perubahan tempat dan waktu.
Tidak hanya sampai di situ, bahkan mereka menolak segala hal yang berasal dari luar Islam meskipun dapat memberikan nilai positif bagi umat Islam dengan argumentasi bahwa hal itu berarti menambah dalam urusan agama (bid’ah). Maka tidak heran jika mereka juga menolak partai politik, demokrasi, dan lain sebagainya karena anggapan bid’ah itu tadi. Lebih parah lagi, mereka menolak zakat dengan mata uang karena dianggap tidak sesuai dengan nas. Bahkan sebagian ulama dari mereka menganggap bahwa harta yang berbentuk uang kertas tidak dikenakan zakat. Alasannya adalah bahwa uang pada masa nabi terbuat dari emas atau perak yang mempunyai nilai tersendiri.
Di sisi lain, terdapat pemikir yang terlalu substansionalis, bahwa segala sesuatu dalam syari’at mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Mereka kurang memperhatikan dan bahkan cenderung berpaling dari nas-nas juz’iyah dengan argumentasi demi kemaslahatan umum dan sesuai dengan maqashid syar’i.
Qaradawi menyebut aliran ini sebagai “neosubstansionalis” mewarisi pemikiran substansionalis klasik yang mengingkari asma Allah dari arti yang sebenarnya.
Mereka tidak mau melihat nas al Qur’ân secara menyeluruh, namun hanya sekedar mengambil nas yang dapat mendukung argumentasi mereka. Padahal nas qoth’i tidak pernah bertentangan dengan maslahat. Menurut Qadhâwî, menghentikan hukuman hudud, membolehkan minuman keras, berzina, menghapuskan zakat, melarang poligami, membolehkan pelacuran, menyamakan pembagian waris atara anak laki-laki dengan anak perempuan, sama sekali tidak mengandung unsur-unsur maslahat. Menurutnya, mereka yang menyeru kepada hal-hal di atas sebenarnya hanya terpengaruhi oleh pemikiran dan budaya Barat. Jika saja para tokoh intelektual Barat tidak mengatakan hal itu tentu mereka juga tidak akan berpendapat seperti itu.[11]
Bagi Qadhâwî, solusi terbaik adalah dengan mengambil jalan tengah. Tidak terlalu tekstualitas dan juga substansionalitas. Dengan demikian akan terhindar dari pengguguran terhadap nas-nas qoth’i tsubût dan dalâlah. Dan hal itu dapat direalisasikan dengan mengaitkan pemahaman nas yang bersifat juz’î dalam kerangka maqashid kullî.[12]
[1] Dr Yûsuf al Qardhâwî, Assiyâsah Assyar’iyah fî Dhou’i Nushûshi al Ayarî’ati wa Maqashidihâ, Maktabah Wahbah hal. 101 dan hal 230
[2] Ibid. hal 272-273
[3] Dr. Abdul Karîm Zaidân, al Wajîz Fî ushûli’l Fikihi. Mu’assasah al Risâlah hal 378
[4] Op. cit. hal. 87
[5] Bin Zaghîbah Izzudin, al maqashid al Ammah li al Syarî’ah al Islâmiyah. Dâru al shofwah hal. 166
[6] Dr Yûsuf al Qardhâwî, Taisîru’l Fikihi Lilmuslimi’l Ma’âshir Fi Dhou’i’l Qur’ân Wassunnah. Maktabah Wahbah hal 42
[7] Dr Yûsuf al Qardhâwî, Assiyâsah Assyar’iyah fî Dhou’i Nushûshi al Ayarî’ati wa Maqashidihâ, Maktabah Wahbah hal 87
[8] Ibid. hal 88
[9] Dr Yûsuf al Qardhâwî, Taisîru’l Fikihi Lilmuslimi’l Ma’âshir Fi Dhou’i’l Qur’ân Wassunnah. Maktabah Wahbah hal 90
[10] Ibid. hal 92-93
[11] Lebih lengkapnya lihat, Dr Yûsuf al Qardhâwî, Assiyâsah Assyar’iyah fî Dhou’i Nushûshi al Ayarî’ati wa Maqashidihâ, Maktabah Wahbah hal 230-286
[12] Dr Yûsuf al Qardhâwî, Taisîru’l Fikihi Lilmuslimi’l Ma’âshir Fi Dhou’i’l Qur’ân Wassunnah. Maktabah Wahbah hal 90