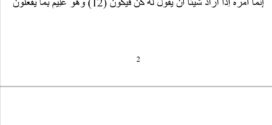Fitur kemenyeluruhan (الكلية : al-kulliyyah, wholeness). Elemen fitur ini ingin membenahi kelemahan ushul fikih klasik yang sering menggunakan pendekatan reduksionis dan atomistik. Pendekatan atomistik terlihat dari sikap mengandalkan hanya pada satu nas untuk menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapinya tanpa memandang nas-nas lain yang terkait. Solusi yang diterapkan adalah menerapkan prinsip holisme melalui operasionalisasi “tafsir tematik” yang tidak lagi terbatas pada ayat-ayat hukum, melainkan juga melibatkan ayat-ayat al-Quran termasuk ayat-ayat yang terkandung di dalamnya pedoman kehidupan sosial dan budaya, sebagai pertimbangan dalam pemutusan hukum Islam secara komprehensif. (Fikih Kebinekaan: 62-63)
Benarkah bahwak ushul fikih klasik hanya sekadar melihat satu nas saja untukmenyelesaikan kasus-kasus yang dihadapi? Ari kita beranjak dari ushul fikih maqashid dan menuju ushul fikih semantik. Kami akan mengambilkan beberapa contoh berikut:
Contoh pertama: Mutlak Muqyyyad
Jika terdapat indikator yang dapat dijadikan sebagai argumen bahwa kata tersebut memiliki ikatan tertentu, maka ungkapan kalimat yang dapat dijadikan sandaran hukum adalah ungkapan yang memiliki ikatan tersebut.
Contoh dalam ungkapan kalimat berikut:
مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ
Artinya: “Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya”. (QS. Al-Nisâ: 11)[1]
Ayat di atas tidak ada batasan ukuran wasiat, namun terdapat batasan dalam ungkapan lain, yaitu hadits Nabi yang diriwayatkan Saat bin Abi Waqqash sebagai berikut:
الثلث و الثلث كثير
Artinya: “Sepertiga, dan sepertiga adalah banyak (HR. Bukhari dan Muslim)”.[2]
Pertama: jika muthlaq dan muqayyad memiliki satu kesimpulan hukum, dan juga sebab diturunkannya lafazh tersebut juga sama, maka dalam kondisi seperti ini, muthlaq dibawa kepada yang muqayyad.
Contoh firman Allah,
إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ
Artinya: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah”. (QS Al-Baqarah:173).
قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
Dalam ayat lain dikatakan: “Katakanlah, “Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi”. (QS Al-An’âm: 145).
Lafazh دَمًا (darah) dalam ayat pertama berbentuk muthlaq sementara dalam ayat kedua berbentuk muqayyad dengan ikatanدَمًا مَّسْفُوحًا (darah yang mengalir). Sementara kesimpulan hukum dari kedua ayat tersebut adalah sama yaitu bahwa makan darah hukumnya haram. Faktor yang melatarbelakangi pengharaman darah juga sama, yaitu madharat yang mugkin ditimbulkan darinya. Maka dalam kondisi seperti ini muthlaq dibawa kepada yang muqayyad. Dengan kata lain bahwa darah yang diharamkan adalah yang mengalir saja. Sementara yang tidak mengalir seperti jantung dan hati tidak diharamkan.
Kedua: hukum dan sebab turunnya nash antara muthlaq dan muqayyad berbeda.
Contoh:
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا
Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya”. (QS. Al-Maidah: 38).
Dan juga firman Allah:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku. (QS. Al-Maidah ayat: 6).
Lafazh أَيْدِي (dua tangan) dalam ayat pertama disebutkan secara muthlaq, sementara dalam ayat kedua disebutkan secara muqayyad, yaitu ditambah dengan ungkapan إِلَى الْمَرَافِقِ (sampai ke siku-siku). Sementara ketetapan hukum dari dua ayat tersebut memiliki perbedaan. Ayat pertama menerangkan tentang hukuman bagi orang yang mencuri, yaitu dipotong tangannya, sementara ayat kedua menerangkan mengenai tata cara berwudhu, yaitu kewajiban membasuh tangan. Sebab diturunkan hukum dalam ayat pertama adalah pencurian, sementara dalam ayat kedua adalah perbuatan yang mesti dilakukan sebelum shalat. Dalam kondisi seperti ini, muthlaq tidak dibawa kepada muqayyad. Namun muthlaq tetap disikapi sebagai muthlaq dan muqayyad juga disikapi sebagai muqayyad. Hal ini disebabkan karena antara kedua ayat tersebut tidak memiliki hubungan sama sekali.
Ketiga: ketetapan hukum yang terkandung dalam nash berbeda, sementara sebab ketetapan hukum sama. Dalam kondisi seperti ini maka ungkapan yang berbentuk muthlaq tetap difungsikan sebagai muthlaq, dan muqayyad juga difungsikan sebagai muqayyad.
Contoh:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ُ
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku”. (QS. Al-Mâ‘idah: 6).
Dan juga firman Allah:
فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ
Artinya: “Lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. (QS. Al-Mâ‘idah: 6).
Maka kesimpulan hukum yang dihasilkan adalah sebagai berikut:
Ayat pertama diwajibkan membasuh kedua tangan dengan diberi ikatan إِلَى الْمَرَافِقِ (sampai siku-siku). Sementara ayat kedua tidak diberi ikatan tertentu, atau lafazh tersebut berbentuk muthlaq. Sebab hukum dari kedua ungkapan tersebut juga sama, yaitu melaksanakan suatu pekerjaan sebelum menunaikan shalat. Dalam kasus seperti ini muthlaq tidak dibawa kepada muqayyad, namun tiap kalimat difungsikan sebagaimana tertera dalam ungkapan kalimat masing-masing.
Keempat: ketetapan hukum muthlaq dan muqayyad sama, namun sebab hukumnya berbeda. Dalam kondisi seperti ini menurut Hanafiyah dan Ja’fariyah, muthlaq difungsikan sebagai muthlaq, dan muqayyad juga difungsikan sebagai muqayyad Sementara menurut Syafi’iyah, muthlaq dibawa pada muqayyad.
Contoh firman Allah mengenai kafarat zhihâr:
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
Artinya: Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak”. (QS Al-Mujadalah: 3)
Dan juga firman Allah dalam kafarat pembunuhan yang tidak disengaja:
وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ
Artinya: Dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah ia) memerdekakan hamba-sahaya yang mukmin”. (QS Al-Nisâ’:92).
Lafazh رَقَبَةٍ (hamba sahaya) dalam ayat pertama berbentuk muthlaq dan dalam ayat kedua berbentuk muqayyad. Argumentasi pendapat kedua adalah bahwa ketetapan hukum dari dua nash tersebut sama, hanya saja nash pertama berbentuk muthlaq dan nahs kedua muqayyad, maka mutlak harus dibawa kepada muqayyad. Hal ini untuk menjaga agar tidak terjadi benturan (ta’ârud) antar nash serta untuk mengkondisikan nash agar selalu serasi.
Sementara argumentasi Hanafiyah adalah bahwa adakalanya perbedaan sebab tersebut yang memicu suatu ayat berbentuk muthlaq sementara dalam ayat lain muqayyad. Jadi dalam ayat pertama memang yang dimaksudkan oleh nash adalah makna mutlak, sementara dalam ayat yang lain, makna yang dimaksudkan nash adalah muqayyad. Contohnya seperti kafarat pembunuh yang tidak disengaja. Lafazh رَقَبَةٍ (budak) diikat dengan lafazh مُّؤْمِنَةٍ (budak yang mukmin). Tujuannya adalah agar hukuman bagi pembunuh lebih berat. Sementara dalam ayat zhihâr, beban kafarat mengenai pembebasan budak tidak diberi ikatan dengan budak yang mukmin. Tujuannya adalah untuk memberikan keringanan hukum bagi suami, juga untuk menjaga kelangsungan pernikahan. Selain itu, membawa muthlaq kepada muqayyad sesungguhnya bertujuan untuk menjaga agar antara dua ayat tidak terjadi benturan (ta’ârud).[3]
Contoh Kedua, Kata Perintah:
Al-amr (kata perintah) memiliki banyak makna, terkadang bermakna wajib, nadb, ibâhah, ancaman, anjuran, meremehkan lawan, doa dan lain-lain. Perbedaan dalam memahami makna dalam satu lafazh, berimplikasi pada perbedaan ketetapan hukum antara para ulama, khususnya ketika tidak terdapat indikator (qarînah) yang menunjukkan makna yang dimaksud. Para ulama bersepakat bahwa bentuk kata perintah dengan berbagai maknanya, tidak memiliki makna yang sesungguhnya (haqîqiy), dalam artian kata perintah (amr) tersebut adalah metafor jika berkaitan dengan sesuatu yang tidak wajib, nadb dan ibâhah. Jadi perbedaan antara para ulama terdapat dalam tiga makna tersebut, yaitu; apakah kata perintah dimaksudkan sebagai petunjuk terhadap tiga makna secara keseluruhan, atau sebagiannya, atau hanya satu di antara tiga makna? [4]
Sebagian ulama berpendapat bahwa kata perintah (amr) memungkinkan untuk memiliki tiga makna karena persamaan lafazh yang digunakan. Makna yang dimaksudkan oleh lafazh dapat diketahui melalui penelitian dan pemilahan makna (murajjah).
Sebagian lain mengatakan bahwa kata perintah (amr) kemungkinan hanya memiliki makna wajib dan nadb saja. Untuk mengetahui yang paling benar di antara keduanya dapat dilakukan sistem pemilahan makna (murajjah).
Sementara imam al-Ghazali mengatakan bahwa sulit untuk diketahui apakah kata perintah (amr) memiliki makna wajib saja, ataukah nadb saja, ataukah memiliki makna ganda (bil isytirâk). Menurutnya bahwa kata perintah (amr) tidak dapat diketahui ketetapan hukum terkecuali dalam kalimat tersebut terdapat indikator (qarìnah)[5].
Secara umum, para ulama berpendapat bahwa kata perintah (amr) hanya memiliki satu dari tiga makna. Dan ketetapan hukum dari padanya dapat diketahui melalui makna yang sesungguhnya (haqîqiy) sesuai dengan makna terapan suatu lafazh. Jika makna tersebut bertentangan dengan makna terapan suatu lafazh, maka kata perintah (amr) mengandung makna metafor (majâz).
Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan satu dari tiga makna yang dimaksud. Sebagian Malikiyah berpendapat bahwa makna yang dimaksud adalah al-ibâhah, karena kata perintah (amr) digunakan untuk meminta agar seseorang melakukan perbuatan tertentu. Dan perbuatan terkecil yang diyakini dapat dikerjakan adalah al-ibâhah. Sementara sebagian Syafiiyah berpendapat bahwa kata perintah (amr) memiliki makna al-nadb, dengan alasan bahwa kata perintah diciptakan untuk meminta pelaksanaan suatu perbuatan.
Sementara sebagian besar ulama berpendapat bahwa kata perintah (amr) menunjukkan makna wajib. Artinya, kata perintah (amr) yang berbentuk muthlaq diciptakan untuk menunjukkan makna tersebut. Dengan kata lain, bahwa makna yang sesungguhnya adalah wajib, sementara makna selainnya adalah metafor (majâz). Maka makna dari kata perintah (amr) dapat berubah dari wajib menuju makna lain jika terdapat indikator (qarìnah) yang menunjukkan pada perubahan makna tersebut. Jika indikator (qarinah) menunjukkan makna nadb maka kata perintah (amr) akan menunjukkan makna nadb dan jika indikator (qarinah) menunjukkan makna ibâhah maka makna yang terkandung dibalik kata perintah (amr) adalah ibâhah.
Contoh ketiga: al-kalâm al-mustaqil al-munfashil
Yaitu kalimat yang berdiri sendiri dan terpisah dari ungkapan kalimat umum.
Contoh:
وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ
Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’”. (QS. Al-Baqarah 228).
Lafazh (الْمُطَلَّقَات) adalah lafazh ‘âm, mencakup semua wanita yang telah ditalak, baik yang sudah digauli ataupun yang belum. Maka masa iddah baginya adalah tiga qurû’. Namun dalam nash lain dibedakan antara yang sudah digauli dengan yang belum, yaitu firman Allah:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka ‘iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya”. (QS. Al-Ahzab: 49)
Kesimpulannya, dari berbagai contoh di atas sebagaimana yang saya sampaikan dalam ushul fikih klasik (semantik), ternyata para ulama tidak hanya melihat satu nas saja dalam menentukan sebuah konklusi hukum. Ayat al-Quran dan hadis nabi adalah satu-kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Memahami satu ayat saja atau satu hadis saja kemudian mengambil kesimpulan hukum akan berakibat fata.
Bisa saja satu ayat bersifat mutlak, namun di ayat lain ternyata ada keterangantambahan yang memberikan qayyad terhadap nas tadi. Atau bisa saja dalam al-Quran, suatu ayat masih bersifat mujmal (umum, sementara keterangan lebih lanjut berada di sunnah nabi.
Bukankah dalam al-Quran hanya sekadar perintah shalat? Bagaimana detail-detail pelaksanaan shalat? Demikian juga dengan puasa, zakat, haji, dalam al-Quran sangat umum sementara detailnya diterangkan oleh hadis nabi. Jadi, tuduhan bahwa rumusan ushul fikih klasik sangat atomistik dan sekadar mengandalkan satu nas saja, terbantahkan dengan sendirinya.
Jika saja Amin Abdullah mau membuka ktab-kitab ushul fikih klasik secara langsung, seperti kitab al-Mankhul karya Imam Ghazali, al-Mahshul karya Imam Ar-Razi, al-Burhan karya imam Haramain dan kitab-kitab ushul lainnya, niscaya beliau tidak akan gegabah mengambil kesimpulan seperti itu. Sayangnya, beliau hanya “kata orang” dengan menukil pandangan orang lain tanpa merujuk langsung kepada ushul fikih klasik. Akibatnya, tatkala orang lain salah dalam memberikan kesimpulan hukum, maka beliau juga ikut salah salah.
[1] Ibid. hal. 286
[2] Imam Muhammad bin Ismail al-Amir al-Yamani al-Shan’ani, Subulu al-Salâm Syarh Bulûghu’l Marâm, ‘Isham Ashshababiti, Ahmad Sayyid, ed, jilid III, tanpa tahun, Dâru’l Hadîts, hal. 153
[3] Dr. Abdul Karim Zaidan, op. cit., hal. 288
[4] Abu al-Husain Muhammad Ibn Ali ibnu al-Thayib al-Bashriy al-Mu’taziliy, Al-Mu’tamad fî Ushûli’l Fiqh, Jilid I, Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, hal, 50, et, aqq
[5] Imam Abu Hamid al-Ghazalîy, Al-Mustashfâ fî Ushûli’l Fiqh, Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, 2000, hal 211.